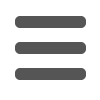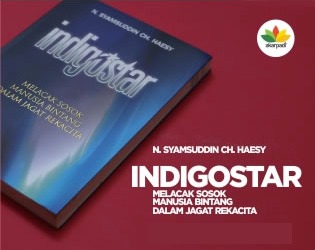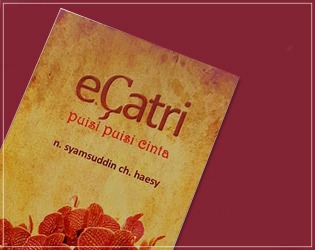Berburu Warisan Sejarah Leluhur

AKARPADINEWS.COM | SEBONGKAH batu dengan ujung melengkung yang menua, masih berdiri di pekarangan rumah keluarga Lord Minto VII, Gilbert Timothy George Lariston Elliot-Murray-Kynynmound, Hawick, Roxburghshire, Skotlandia. Batu itu terpancang telanjang. Tak ada atap, terlebih pelindung.
Balok batu berukuran 160 x 122 sentimeter, setebal 32,5 sentimeter itu, seakan asing dari pemeliharaan. Permukaan kepala batu penuh lumut. Berpupur jamur. Melapuk. Sementara kedua sisinya banyak terkelupas. Aus. Beberapa deret guratan aksara Jawa Kuna di bagian depan (recto) pun tersamar jamur dan lumut.
Batu itu tersohor dengan sebutan Batu Minto. Meski tampak lusuh dan tak terurus, Batu Minto justru mempunyai koneksi kuat dengan empunya kediaman, khususnya sang moyang, Lord Minto I atau Sir Gilbert Elliot Murray-Kynynmound, Gubernur Jendral Inggris untuk India (1807-1813).
Semula, demi memenuhi hasrat akan sejarah, budaya, dan spesies eksotis Jawa, Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Jawa (1811-1816), memerintahkan Kolonel Colin Mackenzie, Kepala Zeni Pasukan Inggris (1811-1813), untuk mengumpulkan segala benda budaya, manuskrip kuno, serta spesies tumbuhan dan hewan. Mackenzie beroleh beragam benda budaya, termasuk dua buah prasasti; Sangguran (928 M) dan Pucangan (1041 M).
Prasasti Sangguran berangka tahun 850 Caka atau 928 Masehi, tercanang atas perintah Raja Mataram Kuna, Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sri Wijayaloka Namestungga. Prasasti tersebut memuat keterangan anugerah Sima atau penetapan daerah perdikan kepada Desa Sangguran (Dusun Kajang-kini), Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Malang. Prasasti Sangguran kemudian tersohor dengan sebutan Batu Minto lantaran menjadi “milik” Lord Minto I.
Sementara, Prasasti Pucangan bertarikh 963 Caka atau 1041 Masehi, merupakan sumber dokumen penting berkait Raja Airlangga (1019-1049). Prasasti berbahasa Sanskerta dan Jawa Kuna ini acap disebut sebagai Batu Kolkata (Calcutta).
Raffles kemudian memberi kedua prasasti tersebut kepada Lord Minto I sebagai hadiah. Prasasti tersebut berpindah tangan melalui jalur laut, bertolak dari pelabuhan Surabaya pada 1813, berlayar menumpang kapal HMS Matilda menuju pelabuhan Kolkata, India. Lord Minto I terkesan dengan hadiah Prasasti Sangguran.

“Saya sangat berterima kasih atas kiriman batu besar dari pedalaman pulau anda (Jawa),” tulis Lord Minto I dalam suratnya kepada Raffles, tertanggal 23 Juni 1813, termuat dalam The History of Java. “Beratnya, setidaknya, tampak cukup menyaingi patung Peter Yang Agung, St. Petersburg (Rusia)”.
Lord Minto I berkehendak, menempatkan prasasti seberat 3,5 ton di puncak perbukitan Minto Craigs, sebelah utara Sungai Tevoit, Skotlandia. Meski berhasil memindahkan prasasti itu ke tanah airnya, Minto gagal bersua kembali dengan prasastinya, Batu Minto.
Enam bulan paska menerima hadiah prasasti, dia dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Inggris untuk India. Dia lantas kembali ke Inggris sembari bergelut dengan sakitnya. Tak mampu bertahan, Lord Minto I akhirnya wafat di Stevenage, 21 Juni 1814, dalam perjalan menuju Skotlandia.
Prasasti Sangguran atau Batu Minto hingga kini terasing dari tempat asalnya. Menua di negeri orang. Menjadi barang usang. “Batu Minto, telah berkurang statusnya, hanya menjadi ornamen taman di daerah perbatasan terpencil dan hampir tidak dapat diakses dari Skotlandia,” tulis Nigel Bullough dkk, termuat The Kolkata (Calcutta) Stone and The Bicentennial of The British Interregnum in Java, 1811—1816.
Setali tiga uang. Prasasti Pucangan atau Batu Kolkata pun bernasib nahas. Batu Kolkata terjebak di gudang nan lembab, hanya bermandi semilir angin dari kipas angin yang berdiri beberapa meter di hadapannya, bersama onggokan barang-barang pada Museum India di Kolkata.
Batu Kolkata memang tak pernah pergi dari India sejak Raffles menghadiahkannya kepada Lord Minto I. Sebagai dokumen penting berkait Raja Airlangga, Batu Kolkata, teramat sia-sia dapat perlakuan sebatas itu.
Usaha pemulangan prasasti bukan kali ini dilakukan. Hari Untoro Drajat, Dirjen Sejarah dan Purbakala (2005-2009), sempat membentuk tim pemulangan Prasasti Sangguran (Batu Mito) untuk berangkat ke London, menjalin koordinasi dengan KBRI London guna bertemu Lord Minto VII. Dalam pertemuan di KBRI, siang 21 Februari 2006, “Lord Minto VII menyatakan tak berkeberatan melepas prasasti tersebut,” tulis Tempo, 4 Mei 2014.

Lord Minto VII ternyata tak bisa seorang diri memutuskan. Dia harus meminta persetujuan dewan pengawas (trustees), pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Selepas berkonsultasi dengan pelbagai pihak, Lord Minto VII lantas berubah pendirian.
Dia menghendaki kompensasi. Di seberang sisi, Hari Untoro menegaskan, sejak awal tim yang berangkat ke London tidak beroleh wewenang untuk membayar atau memberi kompensasi atas pemulangan Batu Minto. Jika membayar kompensasi, lanjutnya, itu berarti mengakui prasasti tersebut milik si pemegang.
Beragam skenario telah dilakukan, namun tak jua mencapai kata sepakat. Usaha pemulangan Prasasti Sangguran pun tutup buku. Lembar baru usaha pengembalian prasasti akhir-akhir ini perlahan mulai menggeliat. Tak hanya Prasasti Sangguran (Batu Minto), juga Prasasti Pucangan (Batu Kolkata). Para akademisi berikut penggiat sejarah lebih awal mengambil inisiatif melakukan kajian terhadap dua prasasti guna pemulangan memori di atas kertas.
Hasrat pengembalian kedua prasasti kembali meninggi lantaran terpicu kisah keberhasilan pengembalian pusaka Pangeran Diponegoro, Tongkat Ziarah Kanjeng Kiai Cakra, pada pembukaan pameran “Aku Diponegoro; Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa, Dari raden Saleh Hingga Kini” pada 5 Februari 2015.
Diponegoro beroleh Kiai Cakra dari seorang warga asal Jawa pada 1815. Sang pangeran acap membawa tongkat itu ketika berziarah ke wilayah pantai selatan Jawa dan Yogyakarta. Simbol cakra memiliki arti penting baginya. Dewa Wisnu berinkarnasi ke-7 sebagai penguasa dunia dengan menggenggam senjata cakra. Sang pangeran, dalam mitologi Jawa, datang sebagai Ratu Adil (Erucakra). Dia pun menggunakan gelar Erucakra, terutama pada tahap awal Perang Jawa.
Tongkat Kiai Cakra berpisah dari sang pangeran pada 11 Agustus 1829, saat dirinya melakukan kampanye terakhir di wilayah Mataram. Tongkat Kiai Cakra jatuh ke tangan Adipati Notoprojo (1803-1855), cucu seorang komandan pasukan perempuan Diponegoro, Nyi Ageng Serang (1769-1855).
Notoprojo kemudian memberikan tongkat itu kepada Gubernur Jenderal JC Baud pada Juli 1834, saat sang gubernur jenderal melakukan perjalanan pertama (tournee) ke wilayah Jawa Tengah. Kiai Cakra selanjutnya bermukim di Negeri Belanda.
Ahli waris JC Baud, Michiel dan Erica, bersedia mengembalikan tongkai Kiai Cakra kepada Pemerintah Republik Indonesia. “Kami berharap bahwa penyerahan tongkat ini menjadi momentum kecil namun penting secara simbolis dalam memasuki era baru dengan saling menghormati, persahabatan, dan persamaan,” ungkap Michiel Baud pada sambutan penyerahan Tongkat Kiai Cakra (5/2/2015).

Tongkat Kiai Cakra bukan satu-satunya cerita sukses pengembalian warisan budaya Nusantara tersimpan pada museum maupun koleksi pribadi di luar negeri. Pusaka Diponegoro lainnya: Tombak Kiai Rondhan dan Pelana Kuda, serta lukisan Raden Saleh bertajuk “Penangkapan Pemimpin Jawa Diponegoro” berhasil pulang ke tanah air pada 1976. Ketiga warisan budaya tersebut semula tersimpan di Museum Veteran Tentara Belanda di Broonbeek, Arnhem, Belanda.
Ratu Juliana yang bertakhta 1948-1980, bersedia memulangkan ketiga benda tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah ketentuan Cultural Accord pada penandatanganan kesepahaman tahun 1969. Kedua pusaka sang pangeran kemudian menjadi koleksi Museum Nasional, sedangkan lukisan Raden Saleh bermukim di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
Pada tahun 1970, Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama budaya dengan Belanda ihwal pemulangan warisan budaya Indonesia. Tiga warisan budaya yang berhasil pulang secara bertahap antara lain; Kitab Nagarakrtagama, Arca Prajnaoaramita, dan Goong Ageung (gong besar) salah satu perangkat Gamelan Sari Oneng Palakan Salak.
Beragam kisah cemerlang pemulangan tersebut, belum cukup menutup ribuan daftar pengembaraan warisan budaya Indonesia di mancanegara. Terdapat Prasasti Watukura (902 Caka) menjadi koleksi keluarga L Norgaard, di Denmark. Ada pula Prasasti Wukayan tersimpan pada Tropenmuseum, Prasasti Sangsang di Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam, Prasasti Guntur koleksi Maritiem Museum, Rotterdam, dan Prasasti Tulangan di Volkenkunde Museum.
Catatan itu belum berakhir, salah satu warisan budaya lainnya, naskah misalnya, tercatat jumlah naskah kuno baik berbahasa Melayu, Jawa, dan bahasa etnisnya di atas 30.000 naskah, tersebar di hampir 30 negara (Kompas, 21 Juli 2000). Belum lagi jumlah benda etnologi, dari 200 ribu benda koleksi Volkenkunde Museum atau Museum Etnologi, Leiden, Belanda, sebanyak 66 ribu benda berasal dari Indonesia.

Pemindahan warisan budaya tanah air memiliki beragam faktor karena pemberian atau hadiah selaik polah Residen Kedua, CL Hartman, memberi tanda mata sejumlah delapan gerobak, memuat 30 batu relief, lima patung Budha, dua patung singa, sejumlah kepala kala, satu pancuran makara, dan sebuah patung raksasa penjaga pintu (dwarapala) kepada Raja Siam (Thailand), Chula-Longkorn, ketika mengunjungi Jawa pada 1840.
Hasil rampasan paska serangan pasukan Inggris ke Kraton Yogyakarta Juni 1812, selama empat hari, menurut Babad Bedhah ing Yogyakarta, merampas berbagai senjata, wayang, 166 naskah Jawa, perhiasan, dan benda-benda paska pameran di luar negeri seperti 4.000 benda etnografi yang tak diangkut pulang setelah mengisi Pameran Kolonial dan Perdagangan Ekspor Internasional di Amterdam pada 1883.
Ribuan warisan budaya Indonesia tersebar di luar negeri, menanti niat dan upaya keras para pemangku kepentingan di tanah air untuk memulangkan benda-benda berharga tersebut ke tempat asalnya.
Konvensi UNESCO tahun 1970 tentang larangan perdagangan internasional dan tranisi ilegal benda peninggalan sejarah, tak mampu mengakomodasi pemulangan warisan budaya Indonesia. Pasalnya, konvensi itu hanya mengatur pencurian atau transisi warisan budaya setelah tahun 1970. Sementara, warisan budaya Indonesia lebih banyak berpindah sebelum tahun 1970, terutama pada masa kolonial.
Tak hilang akal, berkaca pada pengalaman sebelumnya, semestinya usaha pemulangan warisan budaya dapat terwujud melalui jalin kesepakatan terhadap negara tujuan. Lawatan Presiden Jokowi ke Belanda pada April lalu sejatinya menjadi pintu masuk kerjasama bidang budaya, khususnya berkait pemulangan warisan budaya.

Sayang, buah kunjungan Jokowi ternyata hanya menyasar pengelolaan air, penanggulangan banjir, bidang maritim, dan perdagangan serta investasi. Di tanah air, wacana pemulangan warisan budaya justru terganjal adagium purba bahwa bangsa Indonesia tak akan mampu memelihara, akan terbengkalai, dan jadi lahan empuk pencurian sehingga lebih baik tersimpan di luar negeri, lebih terawat. Parahnya, adagium itu meluncur dari mulut pemangku kepentingan.
Apakah bangsa Indonesia tak mampu memberi atap terlebih pelindung, bahkan perawatan berkala untuk kedua batu bersejarah itu? Pasti mampu. Pengembalian warisan budaya tak sekadar memulangkan benda bersejarah, lebih dari itu mengembalikan ingatan bangsa dan pemicu geliat penelitian.
Dirga Adinata