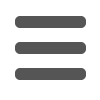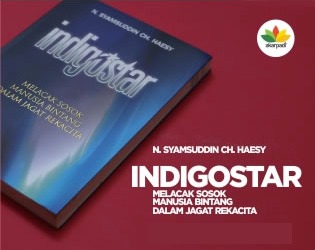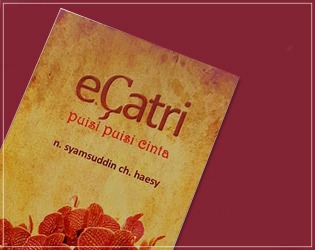Kearifan Cerekang, Konsisten Memelihara Alam

BANYAK nilai yang diwariskan tradisi masa lalu dalam mengelola sumberdaya alam sebagai cawandatu. Di Timur Matahari, khususnya di Sulawesi, setidaknya kita mengenal berbagai tradisi yang berpijak di atas kearifan lokal. Apa yang kita saksikan di Toraja, menjelaskan bagaimana manusia sebagai subyek, bertanggung jawab penuh atas kondisi sumberdaya alam.
Pun demikian halnya dengan masyarakat Bajo, Bissu, Dongi, dan begitu banyak lagi tradisi yang berkembang di kalangan etnis dan sub etnis di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Luwu. Masyarakat Cerekang, adalah contohnya.
Dalam hal melakukan proses transformasi sains dan teknologi, misalnya. Adat istiadat yang berkembang di lingkungan masyarakat Cerekang, mengajarkan kita tentang pentingnya prinsip asasi ‘saling memuliakan.’
Adat yang mengajarkan siapa saja untuk menghormati nilai-nilai adat tradisi yang diyakini masyarakat, agar hidup berjalan secara harmonis. Saling menguatkan satu dengan lainnya.
Melakukan proses transformasi dengan mengabaikan nilai yang telah berurat akar di tengah masyarakat, akan menimbulkan dampak yang buruk. "Masussatu narekko kaca mallise' melo iliseki", tak mudah mengisi gelas yang telah berisi, ungkap masyarakat Cerekang. Masyarakat Cerekang berada di desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
Nilai kearifan lokal yang tersurat dan tersirat dari prinsip nilai masyarakat Cerekang, itu menunjukkan ada dan kuatnya komitmen (yang dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten) dalam memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sebagai the real environment.
Dalam konteks demikian, proses transformasi sosial, termasuk transfer of science and technology, tak boleh mengabaikan nilai adat yang telah hidup turun temurun. Tak hanya sebatas bagaimana mengelola hutan dan alam lingkungan, dengan tetap berorientasi kepada kondisi sumberdaya alam ‘semula jadi’.

Kearifan lokal masyarakat Cerekang, mengingatkan kita, untuk menentukan point of view mengelola sumber daya alam. Mulai dari menata-kelola hutan, sebagaimana nampak nyata di pangngale' ada' tomatoa' yang disebut Karama'. Hutan adat yang tak boleh dijamah. Hutan yang dipelihara untuk sepenuhnya menjadi tiang sangga kelestarian alam yang dalam bahasa kekinian kita sebut sebagai hutan lindung. Berbeda dengan hutan budidaya.
Secara panteistik, sesuai dengan realitas budaya sinkretik, yang berkembang di lingkungan masyarakat Cerekang, kawasan Karama' diyakini sebagai tempat semayam orang-orang mulia, mulai dari Bhatara Guru dan Sawerigading, yang kisahnya pun hanya boleh dituturkan pada momen yang sangat tepat.
Karena merupakan tempat turunnya Dewa dari ‘Dunia di Atas’ dan beberapa keturunannya, maka tak hanya manusia yang menjaga Karama’, ini. Melainkan juga makhluk lain. Jin, dan binatang buas (buaya, misalnya). Karenanya, di kawasan ini berlaku hukum alam. Siapa melanggar, akan mendapatkan abala' alias bencana. Minimal, dilahap buaya.
Kearifan masyarakat Cerekang mengelola hutan, khasnya hutan adat, akhirnya tak berhenti hanya karena berbagai ritus yang memandu manusia menjalani tata krama berhubungan dengan alam. Melainkan juga bagaimana manusia mesti memosisikan dirinya dalam keseluruhan konteks hubungan manusia - alam - dan Tuhan.
Dalam konteks ritual, dikenal Mappaenre Ota. Ritual yang digelar untuk mengharung hasrat dan keinginan manusia. Akan halnya Mappasolonggang Buaja, diperuntukkan bagi keselamatan insaniah tersebab terbangunnya harmonitas manusia, alam, dan Tuhan.

BERSEKUTU DENGAN ALAM ADALAH KONSEP HIDUP MENARIK DARI CEREKANG
Ritual ini mengajarkan kita tentang hakekat eksistensi manusia dalam keseluruhan konteks hubungan Manusia – Tuhan – Alam, sebagai taro puang atau ciptaan Tuhan, yang mesti hidup berdampingan dalam keselarasan hidup dengan gunung, hutan, sungai, dan binatang (termasuk binatang buas).
Seandainya di kawasan Karama' terdapat potensi tambang yang amat luar biasa, jangan coba-coba mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. Masyarakat Cerekang akan berjuang mempertahankan daerah itu untuk tidak diganggu.
Tak hanya karena ada dimensi budaya yang sakral di dalamnya. Lebih jauh dari itu, karena kawasan hutan ‘Karama' merupakan titipan Tuhan yang tak boleh diganggu manusia, bila tak hendak menerima bencana. Inilah prinsip keseimbangan, bagi harmoni kehidupan manusia – alam dengan Tuhan. Tradisi yang berkembang di Cerekang, memberi isyarat tentang nilai fundamental hubungan harmonis tersebut.
Sure’ I La Galigo, yang dituturkan ulang secara tekstual oleh Kern (1939), menunjukkan, bagaimana tradisi budaya masyarakat lokal berinteraksi dan memengaruhi sifat, karakter, bahkan aura budaya masyarakat. Sure’I La Galigo adalah kisah sohor yang menuturkan kesepakatan para dewa langit, mengutus Bhatara Guru untuk mengelola dunia. Lalu mempertemukannya dengan Nyilitomo, putra Ri Selleng di pertiwi (dunia bawah), hingga berputra Batara Lattu', penguasa perdana Tana Luwu.
Nilai-nilai itu, antara lain: nilai religius, sinkretisme budaya berbasis animisme dan dinamisme, serta konsep prima kausa eksistensi manusia - dari sesuatu yang gaib menjadi riil. Lantas, hubungan relasi antara manusia dengan makhluk lain di wilayah mulatau (bumi). Termasuk di dalamnya mitologi.

GADIS-GADIS KECIL DI BALIK JENDELA RUMAH DI CEREKANG
Masyarakat, diungkapkan Ibnu Khaldun, tak bisa dibebaskan dari perkembangan nilai-nilai demikian. Termasuk bagaimana mereka memperlakukan (mengolah dan memelihara) sumberdaya alam yang terkandung di dalam bumi tempat mereka hidup. Inilah yang membangun kesadaran, meski secara bertahap, tentang 'kepemilikan' atas alam beserta isinya.
Ketika datang masyarakat 'luar' dengan pengetahuan dan teknologi untuk mengolah 'kekayaan' alam, yang pertama terbetik, bukanlah bagaimana cara mengolah. Melainkan: siapa mengolah apa di wilayah kepemilikan. Secara sosiologis, hal ini menjelma dalam beragam bentuk, yang sering kali dinyatakan sebagai bukti kebergantungan.
Seringkali persepsi ihwal ketergantungan masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam, lari ke luar konteks. Karena itu, para investor dan pengusaha pertambangan, perlu meluruskan kembali persepsi, dengan mengenali lebih dalam dimensi nilai yang lahir, tumbuh, dan berkembang di daerah tersebut.
Cara terbaik, meski memakan waktu, adalah mengembalikan 'rasa kepemilikan' mereka melalui proses transformasi yang sistematik, terkelola, terukur, dan berkesinambungan. Salah satunya, melalui proses pendidikan. Pendidikan inilah yang akan mendorong masyarakat melahirkan local genius dengan potensi dayacipta yang lebih visioner tentang manajemen sumberdaya alam atau resources governance. Masyarakat, yang sesuai peradaban moderen, sekaligus mampu menjangkau dimensi nilai budaya masyarakatnya.
Kita boleh melihat, apa yang terdapat di kalangan masyarakat Cerekang, Dongi, dan beragam anak suku di Luwu Timur dan Morowali, merupakan ekspresi konkret, bagaimana seharusnya manusia membangun peradaban yang karib dengan lingkungan alamnya. Sekaligus sebagai datu pemelihara alam. Beranjak dari realitas kultural semacam ini, manusia sungguh mengenali fungsinya sebagai datu di atas muka bumi, sebagai khalifatullah fil ardh. Bukan justru sebagai penguasa atas alam, sebagaimana tersimpan di benak manusia-manusia, yang dulu memicu perseteruan di berbagai wilayah kepulauan Nusantara. Khususnya di wilayah Laut Sulawesi. |