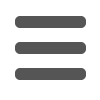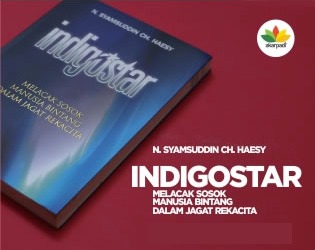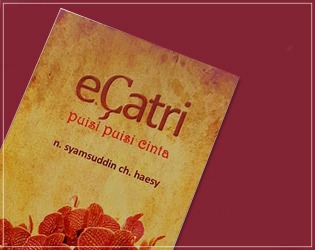Tolikara Mengubur Duka

AKARPADINEWS.COM | WARGA Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, mengubur duka. Rabu, (22/7) lalu, perwakilan komunitas Muslim dan pimpinan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara sepakat berdamai setelah insiden kekerasan komunal meletup pada Jum'at, 17 Juli 2015. Warga juga bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar. Situasi di sana berangsur-angsur kondusif. Aktivitas warga berdenyut lagi. Para pedagang telah kembali menggelar lapak dagangannya.
Jackson Johan, warga Muslim berharap, perdamaian dapat berimbas bagi keamanan di Tolikara. "Asal jangan ada yang terprovokasi. Kita masih khawatir apalagi dalam waktu dekat ada pemilihan kepala daerah (Pilkada)," kata pria kelahiran Jayapura, tetapi keluarga besarnya berasal dari Sulawesi Selatan kepada BBC Indonesia, Kamis (23/7). Menurutnya, sebelum insiden, warga Muslim di Tolikara tidak pernah konflik dengan warga Kristen yang mayoritas.
Bupati Tolikara Usman Wanimbo juga memastikan kondisi Tolikara sudah kondusif. "Aktivitas warga sudah kembali normal," ujar Usman di Jayapura seperti dikutip Antara, 23 Juli 2015.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno juga menegaskan kondisi Tolikara sudah laksana semula. "Pembangunan kembali dilakukan oleh masyarakat bersama TNI dan Polri," jelas Tedjo saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/7).
Insiden Tolikara telah membangkitkan simpati dan kesadaran untuk menyuarakan perdamaian dan membantu para korban. Semua prihatin, menyesalkan tindakan kekerasan komunal di Tolikara. Insiden Tolikara harus menjadi pelajaran dan diharapkan makin menyadarkan penghuni negeri ini jika tindakan anarkis hanya menyisakan darah dan air mata.
Sesama anak bangsa, harus menyadari pentingnya toleransi guna mengukuhkan kebersamaan dalam bingkai keanekaragaman suku, agama, maupun budaya sebagai realitas sosial bangsa Indonesia.
Insiden Tolikara diharapkan tak lagi terulang. Karenanya, pemerintah dan aparat didesak untuk menegakan hukum secara adil terkait pengusutan insiden Tolikara.
"Setiap pelaku kerusuhan dan pengerusakan yang menimbulkan korban harus diproses secara hukum, termasuk aktor intelektualnya, termasuk menindak aparat keamanan yang menyalahi prosedur,” tegas Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Agil Siraj usai bertemu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Negera, Jakarta, Kamis (23/7).
Agil juga mengingatkan pemerintah dan semua pihak mengantisipasi agar insiden Tolikara tidak merambah ke daerah lain. Dia khawatir, jika ada provokasi yang memancing aksi balas dendam.
Kekhawatiran itu bisa menjadi kenyataan jika para pihak yang terlibat konflik tidak segera melakukan rekonsiliasi. Karenanya, Aqil mengimbau semua tokoh agama, adat, masyarakat, maupun pimpinan ormas keagamaan, dan masyarakat untuk meningkatkan dialog.
Pemerintah juga diharapkan segera merehabilitasi rumah ibadah, memperbaiki fasilitas umum, termasuk menanggung nasib para korban.
Pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden itu juga dihadiri cendekiawan muslim Azyumardi Azra, Ustaz Yusuf Mansur, tokoh NU Slamet Effendi, Uskup Agung Suseno, Ketua PGI Pendeta Henriette Tabita Lebang, Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana, Sekjen Walubi, Alex Tumondo, perwakilan tokoh agama Hindu, dan sejumlah pimpinan ormas keagamaan.

Meredam konflik komunal seperti yang terjadi di Tolikara tidak sekadar menebar himbauan, arahan, dan bantuan rehabilitasi saja. Perlu pendekatan yang komprehensif, baik penegakan hukum dan keamanan maupun pendekatan sosial dengan melihat realitas objektif yang menjadi akar konflik. Prosesnya pun harus dilakukan secara berkelanjutan.
Konflik dalam masyarakat sebenarnya tidak meledak begitu saja tanpa rangkaian latar belakang masalah. Informasi mengabarkan jika kekerasan komunal di Tolikara diduga karena kekecewaan massa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terkait pengabaian surat yang ditujukan kepada kaum muslim di Tolikara yang isinya melarang sholat Ied dan mengumandangkan takbir. Larangan itu diterbitkan lantaran bertepatan dengan adanya kegiatan GIDI.
Dalam surat itu, Badan Pekerja Wilatah Toli (BPWT) GIDI memberitahu jika pada tanggal 13-19 Juli 2015 ada kegiatan seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional. Karenanya, GIDI melarang perayaan lebaran tanggal 17 Juli 2015 di Tolikara. GIDI juga melarang muslimat memakai hijab. Surat itu ditandatangani tanggal 11 Juli 2015 oleh Ketua Wilayah Toli Pdt Nayus Wenea, S Th dan Sekretaris Pdt Marthen Jingga, STh MA.
Belakangan, surat tersebut disebut-sebut ilegal. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang menolak isi surat edaran tersebut karena melarang kegiatan beribadah umat beragama lainnya. "Surat itu bukan suara PGLII dan tidak mewakili umat Kristen," ujarnya kepada pers di Gedung PGI, Jakarta Sabtu (18/7).
Aparat keamanan pun dituding tidak tanggap dalam mendeteksi potensi konflik yang dapat muncul di kala perayaan Idul Fitri karena bertepatan dengan acara ritual kaum Nasrani di Tolikara. Pasalnya, surat itu sudah diedarkan sebelumnya. "Jika sudah ada surat edaran pada 17 Juli, seharusnya dapat dicegah sejak awal sehingga tidak sampai terjadi keributan," ujar Ronny. Tudingan itu dibantah Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende.
Insiden Tolikara sebenarnya tidak perlu terjadi. Selama ini, pemerintah maupun tokoh agama dan masyarakat lebih sibuk melakukan tindakan tatkala konflik sudah terjadi dan korban berjatuhan. Pola penangananya pun masih terfokus pada konflik-konflik terbuka, tidak memusatkan perhatian pada antisipasi konflik (pra konflik).
Penyelesaian konflik pun dilakukan secara instan, tidak berkesinambungan, dan tidak menyentuh akar persoalan sehingga seringkali menyisahkan api dalam sekam. Ke depan, penting dilakukan pengelolaan konflik berbasis pengetahuan lokal dengan menguatkan peran institusi lokal. Hal itu lebih baik dibandingkan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak dari luar masyarakat, yang belum tentu paham betul akar persoalan. Alih-alih ingin meredam situasi, justru menebar persoalan baru.
Suatu komunitas masyarakat sejatinya bukanlah sekumpulan orang-orang bodoh yang hanya manut jika mendapatkan perintah. Suatu komunitas sebenarnya telah hidup dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Karenanya, hampir di semua komunitas memiliki kearifan lokal (local wisdom).
Kearifan lokal merupakan warisan para leluhur, baik berupa tata nilai kehidupan yang terintegrasi dalam religi, budaya maupun tradisi. Dalam sebuah komunitas, kearifan lokal biasanya menjadi rujukan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal, mereka mampu bertahan hidup dengan segala masalah yang dihadapi.
Konflik sebagai realitas sosial harus dikelola dengan basis pengetahuan lokal. Peran itu dapat dilakoni insitusi lokal sebagai instrumen yang menggerakan sistem sosial dalam sebuah komunitas. Keberadaan institusi lokal atau juga bisa disebut institusi sosial yang di dalamnya mengandung norma-norma dan nilai-nilai sosial itu sangat penting dalam mempertahankan keserasiaan sosial dan untuk memenuhi tujuan maupun kebutuhan masyarakat.
Dengan kata lain, institusi lokal menjadi acuan atau suatu prosedur yang mengontrol tindakan dan perilaku individu dan masyarakat agar sejalan dengan pola-pola yang sudah mentradisi maupun yang dipaksa bergerak berdasarkan ekspektasi bersama.
Keberadaan nilai-nilai dan norma sosial sebagai peraturan dan adat istiadat harus dipertahankan atau dimodernisasi sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat sehingga berfungsi menjadi instrumen mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat, yang apabila dilanggar akan dijatuhi sanksi sosial yang derajatnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
Di sinilah pentingnya penguatan institusi lokal dalam suatu masyarakat yang rawan konflik. Lembaga swadaya masyarakat bersama pemerintah setempat memiliki peran melakukan pendampingan dengan tujuan memperkuat institusi lokal. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang kondisi masyarakat juga perlu dioptimalkan perannya untuk meningkatkan komitmen masyarakat mengubah perilaku destruktif yang mengikis harmoni sosial.
Penguatan institusi lokal juga sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berakar sesuai dengan karakteristik masyarakat sendiri. Dengan begitu, masyarakat lebih berdaya dalam melakukan fungsi kontrol, sekaligus meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berinteraksi sosial, tanpa harus merusak tatanan nilai yang ada.
Institusi lokal dapat menjadi instrumen menyemaikan kohesivitas sosial, meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab kolektif dan solidaritas sosial. Hal itu dapat terwujud apabila institusi lokal intensif melakukan sosialisasi nilai-nilai yang memperkokoh rasa saling percaya (trust) dan membangun kesadaran masyarakat dalam mempertahankan kohesi sosial.

Konflik di masyarakat juga bisa terjadi lantaran lemahnya internalisasi nilai dan norma kepada masyarakat yang perannya dapat dilakukan tokoh agama maupun masarakat. Insiden Tolikara sejatinya bukan budaya masyarakat Papua. Pasalnya, seperti yang dinyatakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya, baru kali ini konflik terjadi. Budaya masyarakat Papua tidak mengajarkan saling menganggu, apalagi membakar rumah ibadah saat berlangsung ibadah. Menurut Lenis, saat hari raya, masyarakat Papua sangat harmonis. Di kala Idul Fitri, masyarakat menggelar syukuran, begitu sebaliknya. "Kristen dan Islam berdiri dan berdoa bersama," kata Lenis yang juga menjabat Staf Khusus Kepresidenan kepada wartawan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Sabtu (18/7).
Kerukunan di Tolikara sebenarnya sudah terpupuk sejak lama. Menurut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua, Tony Wanggai, hubungan antara komunitas Kristen dan Islam sudah terbangun sejak jaman Kesultanan Tidore. Masuknya agama Kristen di Tanah Papua pada 5 Februari 1855 tidak terlepas dari peran Kesultanan Tidore yang menganut Islam.
Artinya, hubungan antar agama yang berbeda telah terjalin lama di Papua. Maka, sangat disayangkan solidaritas, toleransi yang sudah dipupuk sejak lama ternodai lantaran perbedaan pandangan dan kurangnya komunikasi. Nilai-nilai solidaritas dan toleransi yang sudah dipupuk sejak lama itu harus dibangkitkan lagi.
Konflik dalam masyarakat juga harus dipahami sebagai implikasi perbedaaan norma dan nilai maupun pandangan serta kepentingan antarkelompok dalam masyarakat. Perbedaan itu jika dibiarkan dan tidak ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menghormati perbedaan, maka rawan memicu eskalasi konflik.
Dengan demikian, institusi lokal, tokoh agama, dan masyarakat, memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan keselerasan sosial. Kemampuan tokoh agama dan masyarakat dalam mengorganisir dan mempengarui masyarakat sangat penting perannya dalam proses memediasi dan membangun konsensus sebagai solusi menjawab persoalan yang mengusik toleransi. Mereka juga memainkan peran penting agar semua pihak yang terlibat konflik bersama-sama mengawasi pelaksanaan konsensus guna mengembalikan integrasi.
Tokoh masyarakat dan agama juga dapat melakoni peran sebagai penghubung antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dengan masyarakat setempat yang benar-benar terkena dampak akibat konflik. Dalam konteks ini, pemerintah maupun LSM perlu melakukan pendampingan sosial yang diarahkan agar para stakeholder memiliki kemampuan dalam mengelola konflik dengan baik, sekaligus memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalah-masalah sosial.
Insiden di Tolikara besar kemungkinan karena tidak berfungsinya institusi lokal dalam meredam disharmoni sosial yang telah muncul sebelum insiden terjadi. Kekecewaan yang tak diredam, lama kelamaan menunjukan peningkatan ekskalasi sehingga berujung anarki tatkala ada momen-momen tertentu. Kekecewaan yang dibiarkan dapat berubah menjadi anarki jika disulut provokasi.
Asumsi tersebut bisa jadi benar jika sebelum insiden kekerasan komunal terjadi, hubungan antara komunitas Islam dengan komunitas Kristen di Tolikara kurang berlangsung dengan baik dan menyimpan konflik tersembunyi (laten conflict).
Suara-suara kekecewaan, protes, maupun resistensi yang disuarakan salah satu kelompok seharusnya sejak dini diredam sehingga menciptakan pola interaksi dan relasi antarkomunitas yang dinamis. Konflik laten pada dasarnya dapat berkembang menjadi konflik terbuka (manifest conflict) jika tuntutan yang disuarakan salah satu pihak tidak diakomodasi dengan baik atau dikelola oleh institusi sosial.
Di sinilah pentingnya mengembangkan manajemen konflik dalam mengelola perbedaan pandangan, agama dan kepercayaan, termasuk tatanan nilai dan norma yang diadopsi suku-suku dalam sebuah masyarakat. Konflik juga dapat meletup kapan saja tatkala ada upaya mengejar kepentingan, termasuk pembiaran terhadap diskriminasi, kemiskinan, penindasan, maupun lemahnya penegakan hukum.
Di sinilah pentingnya upaya deteksi dini dalam mencermati dinamika dalam kehidupan masyarakat. Ketidakmampuan institusi lokal maupun institusi sosial (lembaga adat, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah) dalam mengelola konflik dapat terlihat ketidakmampuan dalam mendorong pola interaksi yang baik sehingga memicu prasangka sosial (prejudice) dan pengelompokan masyarakat berdasarkan suku dan agama sehingga dapat mengukuhkan stereotip, ego kelompok, dan pandangan yang memandang remeh kelompok lain.
Kondisi demikian akan menghambat interaksi sosial. Ketika prasangka, kecumburuan, kekecewaan dan sebagainya tidak dicairkan dan dibiarkan, maka akan mengakumulasikan masalah, yang rawan diprovokasi untuk melakukan tindakan agresi. Dalam kondisi demikian, pihak lain yang berkepentingan dapat mudah menyusup dengan tujuan memancing di air keruh.
Karenanya, penyelesaian konflik di Tolikara tidak cukup hanya sekadar dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah maupun aparat keamanan saja. Namun, perlu dilakukan penguatan institusi lokal atau institusi sosial dalam mengelola konflik guna mencegah terjadinya kekerasan komunal, mencari solusi tatkala terjadi gesekan-gesekan sehingga keteraturan sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Konflik yang mengemuka di Tolikara bisa jadi juga karena masih lemahnya kepekaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga tak mampu dengan cepat mengantisipasi konflik. Atau, justru sebaliknya, aktor-aktor itu terlibat dalam pusaran konflik.
Mengelola konflik merupakan upaya mengawasi dan mencermati dinamika sosial. Bisa dilakukan dengan mendeteksi konflik, ketegangan sosial, maupun polarisasi dalam masyarakat.
Proses mediasi juga tak cukup hanya melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Namun, perlu ada upaya mengakomodasi suara-suara masyarakat dan memastikan adanya partisipasi serta ruang dialog antara para pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks ini, diperlukan partisipasi. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses menjembatani dialog maupun dalam rangka implementasi, pemantauan dan evaluasi dalam upaya mengembalikan keserasian sosial sebagai konsensus bersama. Partisipasi sangat penting agar masyarakat merasa ikut terlibat dalam proses perubahan. Mereka pun akan merasa dihargai jika aspirasinya diakomodasi.
Pendekatan konsensus perlu dibangun guna mencari kesepakatan, dan bertujuan mencari solusi dari seluruh kelompok kepentingan yang memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda-beda. Untuk mencapai konsensus maka semua pihak harus mengakui dan menghormati pandangan berbeda dari pihak lainnya, lalu melakukan negosiasi untuk menampung perbedaan dan mencapai kesepakatan bersama.
Dengan demikian, menuntaskan konflik di Tolikara tidak cukup sekadar membangun komitmen di level tokoh agama dan masyarakat semata. Namun, konsensus juga harus dinyatakan warga. Mereka harus benar-benar bersedia melaksanakan konsensus yang diterima semua pihak.
Hal itu menuntut para pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan komitmen, menemukan tujuan dan tindakan, serta mengawasi setiap proses yang dijalani. Dengan kata lain, upaya mengembalikan keserasian sosial tidak dapat ditetapkan secara instan.
Harus ada proses yang dilalui, yang kadang memerlukan waktu karena upaya merangkai kembali harmoni sosial harus dipahami sebagai proses menyelami permasalahan, dibicarakan secara berkelanjutan, dan memastikan setiap pihak nyaman menerima keputusan. Meski prosesnya agak kompleks, kesepakatan damai yang ditetapkan lewat suatu proses tersebut, akan memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat.
Karenanya, tidak cukup pemerintah dan para pihak terkait, bahwa kerukunan antaretnis tidak cukup hanya dilakukan lewat perbaikan rumah atau fasilitas umum yang hancur saja. Tidak cukup juga sekadar pembauran maupun adaptasi sosial. Namun, harus dengan cara komprehensif dengan mencermati realitas objektif dan mengindentifikasi disfungsi sistem sosial guna mengidentifikasi akar masalahnya.
Lewat proses dialogis yang melibatkan seluruh stakeholder, maka diharapkan dapat membantu mengidentifikasi secara objektif akar masalah dari konflik. Proses dialog juga dapat menjadi forum bagi kelompok yang bertikai untuk memahami fakta yang utuh dan konsekwensi yang ditimbulkan dari konflik. Proses tersebut juga diharapkan menjernihkan segala kesalahpahaman, sehingga ketegangan sosial bisa dicairkan.
Pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak lain yang menjadi mediator, diharapkan bisa berperan mengarahkan semua padangan dan pendapat agar mengarah pada konsensus yang disepakati semua. Pemerintah maupun LSM atau pihak lain dari luar masyarakat perlu menyadarkan masyarakat tentang implikasi konflik yang menyisahkan kesengsaraan.
Sebagai bagian dari proses integrasi, maka kesepakatan damai tidak bisa dominan dipaksakan dari pihak luar masyarakat. Namun, harus berangkat dari suara-suara masyarakat sehingga rasa memiliki tanggungjawab mengaktualisasikan butir-butir kesepakatan dan memiliki komitmen melakukan aksi kolektif yang konstruktif.

Konflik di Tolikara juga harus menjadi pelajaran bagi insan media. Dalam situasi konflik, media harusnya hadir sebagai mediator, bukan sebagai provokator. Namun, jika mencermati berita yang tersebar ke ranah publik, media turut terjebak dalam pusaran konflik.
Seperti diberitakan, 17 Juli 2015 lalu, sekelompok orang menebar amarah tatkala umat Muslim di sana melaksanakan Sholat Ied, merayakan Idul Fitri 1436 hijriah. Satu orang dilaporkan tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka akibat tindakan anarkis itu. Massa juga membakar puluhan kios yang apinya menjalar, membakar Musholla Baitul Muttaqin.
Insiden itu pun dengan cepat menyebar ke khalayak. Berbagai media berlomba-lomba menyuguhkan konflik Tolikara. Wajar, karena konflik, apalagi yang menyisahkan darah dan air mata, mengandung nilai berita (news value). Namun, tidak semua media peka terhadap dampak sosiologis pemberitaan yang mengeksploitasi fakta dengan motif mencari sensasi, rating (media televisi), maupun jumlah klik semata (media online), tanpa memberikan solusi konstruktif.
Media tentu paham jika bias informasi yang disuguhkan rawan memancing amarah massa yang diklaim sebagai bagian dari solidaritas para korban. Jika informasi yang mengumbar sentimen agama dan suku terus-terusan merambah ke ranah publik, tentu akan membakar kemarahan dan aksi balas dendam.
Saat insiden Tolikara baru terjadi, banyak media melaporkan telah terjadi pembubaran solat Ied dan pembakaran tempat ibadah, tanpa disertai sumber yang representatif.
Masyarakat akhirnya dibuat bingung lantaran dijejali informasi-informasi yang kurang akurat yang tersebar begitu massif di media-media sosial. Karenanya, saat insiden baru terjadi, muncul pertanyaan yang dibakar itu masjid atau musholla? Siapa yang membakar? Dibakar secara sengaja atau rumah ibadah itu terbakar lantaran api yang menjalar dari kios-kios yang terbakar?
Media harusnya menjadi mediator bukan provokator tatkala meliput peristiwa konflik. Keterlibatan media dalam pusaran konflik merupakan bentuk pelanggaran Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK/-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Ketentuan itu menekankan larangan media menebar informasi yang dapat menyulut kekerasan. Dalam situasi konflik, media seharusnya mengedepankan jurnalisme damai (peace journalism). Konflik dalam masyarakat memang merupakan kasuistis yang memiliki nilai berita. Namun, tidak bisa diumbar begitu saja, tanpa mempertimbangkan konsekwensinya.
Sebagian masyarakat Indonesia masih sensitif dalam menyikapi isu maupun fakta yang bercorak sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Karenanya, media tidak bisa hanya mengejar kecepatan menyuguhkan berita, apalagi dengan bahasa-bahasa yang provokatif. Namun, wartawan juga harus memahami akar masalah dan mampu memprediksi dampak pemberitaan seputar konflik di masyarakat.
Jurnalisme damai, pada dasarnya menekankan pentingnya jurnalis menyuguhkan berita-berita damai, konstruktif, positif, tanpa mengabaikan fakta sebenarnya. Jurnalisme damai mengajak media melakoni perannya dalam mendorong dialog antarpihak yang berkonflik, bukan justru terjebak dalam pusaran konflik dengan membeberkan berita yang tidak berimbang, berpihak kepada salah satu pihak saja. Di tengah kondisi yang mulai berangsur-angsur membaik, media diharapkan terus mengawal proses perdamaian di Tolikara.
M. Yamin Panca Setia