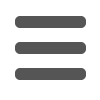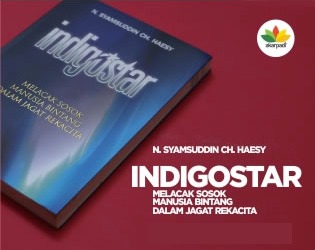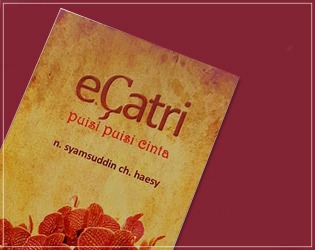Masihkah Kita Sungguh Sebangsa Se-Tanah Air ?

Pertanyaan ringan yang menyentak pada tajuk artikel, ini mengemuka dan tetiba terasa sebagai julekan di kening, ketika disampaikan Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma pada momen penyerahan Penghargaan Akademi Jakarta (AJ) 2025 di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki - Jakarta, Senin (13/10/25) petang.
Penghargaan AJ 2025 diberikan kepada Komunitas Mama-mama Masyarakat Adat Marind Anim (secara virtual) Papua Selatan dan Sastrawan - Jurnalis Martin Aleida.
Dua anggota AJ menjelaskan, untuk sampai kepada para penerima penghargaan, seperti tahun-tahun sebelumnya, anggota AJ perlu waktu panjang, untuk menelusuri data, informasi, dengan berbagai sudut pandang dan perspektif.
Karenanya, Ketua AJ menyatakan, "Apabila hari ini Akademi Jakarta memberikan penghargaan kepada Saudara Martin Aleida dan penghargaan bagi Saudara-saudara dari komunitas Mama-mama Masyarakat Adat Marind Anim di Papua Selatan, sesungguhnyalah merupakan bagian dari pemberian suatu penanda."
Di tengah realitas pertama kehidupan -- dengan beragam informasi brutal yang menyertainya -- yang gamang, tak pasti, ribet, dan mendua sebagai ciri era 'post truth" -- dalam pembahasan nominee penerima penghargaan, berkembang kesadaran untuk menjadikannya sebagai penanda.
"Penanda apa? Penanda tentang siapa yang harus dibela. Penanda tentang siapa yang harus dipedulikan. Penanda tentang siapa yang harus diperjuangkan. Penanda tentang siapa yang harus diberi perhatian sepenuhnya. Penanda tentang siapa yang sudah semestinyalah dimenangkan!" ungkap Seno kemudian.
Penanda yang mesti bermakna, lebih dari sekadar bernilai simpati, empati, apresiasi, respek, dan kemanusiaan yang sekaligus menunjukkan perubahan minda dari aspek hukum ke aspek keadilan, dari aspek estetika ke aspek tamaddun (keberadaban), dan sekaligus mengisyaratkan hakikat perjuangan kemanusiaan.
Dalam sambutannya, Ketua AJ, Seno Gumira Ajidarma menyatakan, penanda dalam pemberian penghargaan AJ 2025, juga mesti merupakan bentuk pengujian : "Apakah kita sungguh-sungguh masih sebangsa dan se-tanah air adanya!"

Perjuangan Lintas Era
Dalam Pertimbangan pemberian penghargaan AJ kepada Komunitas Mama-mama Masyarakat Adat Marind Anim yang dikemukakan Wakil Ketua AJ, Karlina Supelli tampak penanda nyata perjuangan komunitas masyarakat adat Marind (meliputi tujuh marga besar Suku Marind adalah Gebze, Mahuze, Samkakai, Ndiken, Kaize, Basik-Basik, dan Balagaize).
Tak hanya dalam konteks memperjuangkan eksistensi dan dimensi budaya -- yang terkepung dengan perluasan struktur militer dari hanya menjaga perbatasan negara, lantas meluas ke bidang pertanian, penguasaan tanah dan hutan adat, serta pengerjaan proyek dengan beragam istilah sejak pemerintahan kolonial Belanda (1902).
Ketika itu, suku-suku yang mendiami pesisir pantai selatan Papua, termasuk wilayah di sekitar Merauke, daerah Mappi dan Boven Digoel -- dipaksa menerima megaproyek tanpa persetujuan mereka. Lantas, Proyek Padi Kumbe tahun 1955, Mega Proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) seluas 2,5 juta hektar (2010), Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) seluas 1,2 juta hektar dan sekarang Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke seluas 2,29 juta hektar.
Kesemuanya adalah proyek merampas lahan dan hutan adat, menghalangi akses masyarakat adat Marind Anim terhadap sumber daya alam, memicu dan memacu kerusakan lingkungan hidup, disertai dengan berbagai tindakan intimidasi serta kekerasan negara terhadap masyarakat adat.
Kesemuanya memberi penanda, apa yang diperjuangkan mama-mama masyarakat adat Marind Anim merupakan perjuangan lintas era (agraris, industri, informasi, dan konseptual - digital) dan lintas generasi dengan berbagai perubahan orientasi dan nilai yang menyertainya. Bahkan melampaui masa meletiknya gagasan tentang negara (1908) dan gagasan kemerdekaan berpemerintahan sendiri -- zelfbestuur -- diluahkan (1916).
Karlina mengemukakan, "AJ memberikan Penghargaan kepada Komunitas Mama-mama Masyarakat Adat Marind Anim - Papua, sebagai penghormatan dan dukungan terhadap kegigihan mereka memperjuangkan terwujudnya keadilan budaya dan keadilan ekologis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keadilan sosial dan hak asasi manusia."
Mama Yasinta Moiwen yang mewakili komunitasnya menerima penghargaan tersebut secara virtual merespon dengan suara nurani, "Kami masih (akan) terus ada di atas tanah kami..., (walaupun) saat ini kami dalam ancaman akibat proyek strategi nasional - PSN - dua juta hektar.. yang hari ini telah terbukti merampas ruang hidup mereka."
Konsistensi untuk terus memekik, kendati "Saat ini pemerintah DPR, DPD, Gubernur, Bupati, dan Kementerian terkait tidak mendengar suara dan aspirasi kami. (Demikian juga) Majelis Rakyat Papua juga tidak membela kami. Kami ditinggalkan sendiri. Hutan tempat kami mencari makan digusur. Lingkungan kami digusur, tempat hewan dan tanaman obat-obatan. Semua menjadi hancur karena proyek strategis nasional."

Melepaskan Belenggu
Untuk penghargaan AJ kategori perseorangan yang diberikan kepada Martin Aleida, menurut Jeffry Alkatiri -- anggota AJ dalam ucapan pengantar -- mengemuka penanda tentang konsistensi dan konsekuensi seorang sastrawan - jurnalis dalam berkarya.
Martin yang sempat menjadi jurnalis Harian Rakyat dan kemudian menjadi banduan -- tak sampai setahun -- dalam tahanan militer, dan mengeksplorasinya menjadi karya sastra (cerita pendek, esai, dan novel).
"Hampir semua ceritanya didasarkan atas pengalamannya dan juga pengalaman dari para korban aksi berdarah 65 yang ditemuinya dan didengarnya dari para saksi mata. Pada masa itu, hampir semua profesi terkena dampaknya, termasuk para penulis, pegiat teater, musisi, perupa, dalang, buruh, petani, apalagi ABRI, dan pegawai negeri," ungkap Jeffry.
Selepas dari kamp konsentrasi militer -- berkat surat wasiat ayahnya yang hendak berangkat ibadah haji dan surat cinta kepada kekasih yang kemudian menjadi istrinya sampai kini -- , Martin sempat bekerja serabutan -- antara lain sebagai pekerja tambak di Ancol -- dan macam-macam pekerjaan yang masih diingatnya sampai sekarang.
Tahun 1969, menurut Jeffry, Martin memberanikan diri untuk menulis cerpen yang dikirimkannya ke majalah Horison. Setelah merasa percaya diri, dia melanglang menjadi reporter di beberapa media, antara lain di majalah Ekspres (1970), majalah Tempo (1971 - 1983), lalu di mingguan olahraga Bola (1984). Pada tahun 1982 - 1983, ia pernah menempuh studi linguistik di Georgetown University, Washington D.C, Amerika Serikat.
Pada awal era keterbukaan Reformasi 1998, menurut Jeffry, dia terpanggil untuk mengangkat peristiwa kelam tahun 1965 - 1970-an dalam cerita- cerita pendek dan memoarnya, sebagai bentuk kesaksian terhadap kekejaman rezim militer Orde Baru yang baru saja tumbang.
Jeffry juga mengungkap, bagi Martin Aleida, menulis adalah membebaskan dan melepaskan belenggu, terutama untuk dirinya sendiri dari trauma kelam aksi 1965-1970-an. Atas dasar itu juga, Martin diminta sebagai saksi dalam sidang International People’s Tribunal, 10 - 13 Oktober 2015, di Den Haag, Belanda.
Merujuk pada artikel Chris Wibisana (2023), “Trilogi Martin Aleida: Jalan Lain Meraih Keadilan” dalam Jurnal Prisma. Vol, 42, No. 1, Jeffry mensitir, "Bahasa verbal dalam cerita-cerita pendek Martin menghadirkan tragedi dengan narasi ironi yang dihadirkan melalui judul maupun kerangka cerita yang memperkuat argumentasi bahwa pengungkapan tragedi tidak hanya menggambarkan keadaan yang harus dikenang dan menjadi bagian memori kolektif, melainkan juga perlawanan ideologis dan konfrontatif terhadap kebenaran tunggal yang dilegitimasi negara.

Belajar Solidaritas dan Kesetiaan
Jeffry mengungkap, Martin yang sering menulis di meja dapur sambil memasak, memerlukan kesabaran untuk menunggu agar pesannya sampai kepada pembaca, seperti air yang mengalir dan tumpah di lubuk hati dan di benak para pembacanya lewat koran, majalah, medsos, ataupun sekarang lebih banyak dalam bentuk buku.
Buku baru Martin -- dalam cetakan kedua berkisah tentang para eksil di Eropa (Kompas, 2025) -- ungkap Jeffry, mengumpulkan cerita 19 orang Indonesia yang dipaksa dan terpaksa kehilangan tanah air sebab paspor mereka dicabut, sehingga mereka harus klayaban mencari tanah air yang baru karena kewarganegaraan Indonesia mereka dilenyapkan oleh pemerintah Orde Baru.
Saat menyampaikan ucapan penerimaan selepas berdiri di atas atas kursi roda, Martin mengemukakan, "Sungguh saya merasa dimuliakan terpilih sebagai penerima penghargaan Akademi Jakarta untuk tahun 2025 ini."
Ia lantas mengungkapkan, "Saat pertama kali saya mengangkat pensil dan menulis di atas kertas polos, lebih setengah abad lalu, satu-satunya harapanku adalah bahwa saya dibaca. Saya tak tahu siapa orang pertama yang membaca hasil renungan saya itu. Jelas, bukan di antara buruh-buruh pabrik kapur yang berteriak bersinandong ke seberang Sungai Asahan, memanggil-manggil sampan perusahaan supaya datang menyeberangkan mereka."
Dari situlah, menurut Martin, awal hubungan batinnya dengan mereka-mereka yang bergelut dengan hidup - pergumulan yang keras tapi romantis. "Dari mereka juga saya belajar tentang solidaritas dan kesetiaan pada kerja yang sudah jadi pilihan," ungkapnya.
Sebagai penulis, ungkapnya, harapan tertingginya hanyalah sekadar dibaca. Dibaca! Namun, tak menyangka Akademi Jakarta memberikan penghargaan yang tak pernah muncul meskipun dalam angan-angannya. "Pertimbangan Akademi adalah bahwa saya dengan gigih '... mewakili suatu kelompok yang sekali-sekali saja disebut.' Ya, sekali- sekali saja. Mungkin setahun sekali. Tetapi, kelompok atau golongan mana?" ujarnya.
Martin melanjutkan. "Adalah keyakinan saya, bahwa takdir sastra memang tak bisa lain kecuali berpihak pada korban. Kalau tak salah ingat, pada 1972,?di Teater Arena, yang dulu berdiri di dekat tempat kita bertemu sekarang," katanya.
Ketika itu, jelasnya, dibahas kumpulan 13 cerita pendek yang disusun Harry Aveling. Ketiga belas cerita pendek dengan latar 1965 itu menumpahkan empati pada korban. Bertolak belakang secara dramatis dengan sikap yang berada di luar sastra, mereka yang malahan bertempik- sorak merayakan begitu banyaknya manusia yang dibinasakan dengan keji. Bengawan dan sungai seperti tumpat oleh sesaknya jenazah korban yang dilemparkan begitu saja ke arus air yang tak berdosa.
"Penghargaan Akademi ini lebih memperkokoh kegigihan saya, tegak lurus dalam bersikap. Natura yang menempel padanya akan saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk menopang kaki saya supaya tegak dan melangkah memikul beban yang tertumpang pada Penghargaan ini," tukasnya. | haedar